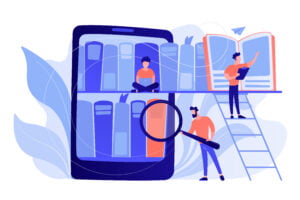Oleh: Ahmad Rizky Mardhatillah Umar*
DINUN.ID Jika anda pergi ke Kalimantan Selatan, sempatkanlah ke Kalampayan, sebuah desa kecil di Kabupaten Banjar. Di sana, bersemayam seorang ulama besar yang penting dalam sejarah berkembangnya Islam di tanah Banjar: Syekh Arsyad al-Banjari. Setiap tahun haul-nya diperingati, makamnya diziarahi, dan kitab-kitabnya, terutama Sabilal Muhtadin, dipelajari oleh santri-santri di Indonesia hingga ke Thailand Selatan.
Berbicara “Islam Banjar” (ini jika kita sepakat untuk menggunakan term “Islam Nusantara” yang sedang digaungkan oleh kaum Nahdhiyin) memang takkan terlepas dari figur Syekh Arsyad. Tak dapat dipungkiri, Syekh Arsyad memberikan warisan tradisi intelektual keagamaan yang sentral dalam perkembangan sejarah Islam di tanah Banjar. Ia bukan hanya seorang ulama “lokal” di tanah Banjar, melainkan juga seorang intelektual yang punya kontribusi signifikan dalam membangun tradisi pengetahuan keagamaan nusantara, bahkan hingga Asia Tenggara.
Tercatat beberapa penulis seperti Azyumardi Azra atau Noorhaidi Hasan menghargai kiprahnya dalam membangun tradisi Islam khas nusantara. Oleh sebab itu, penting untuk mengupas kiprah intelektual Syekh Arsyad secara lebih mendalam di tengah arus wacana keagamaan yang sarat nuansa saling menyalahkan dan mengkafirkan.
Ulama Intelektual Meski banyak yang memperingati haul Syekh Arsyad sebagai seorang ulama besar, tak banyak orang yang mengkategorikan Syekh Arsyad Al-Banjari sebagai seorang intelektual. Kategori “intelektual” yang saya maksudkan intelektual di sini adalah kategori yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai “intelektual profetik” –mereka yang memiliki pengetahuan dan mengembangkan aktivitas berpengetahuan dengan semangat mewarisi amanat kenabian, yaitu membawa manusia dari zhulumaat (kebodohan, kemiskinan, ketertindasan) menuju nur (pengetahuan, kemajuan, pembebasan).
Sisi-sisi intelektualitas Syekh Arsyad ini kerap terpinggirkan oleh kultus individu yang berlebihan oleh banyak orang di tanah Banjar. Akibatnya, proyek intelektual yang sebenarnya sudah dirintis oleh Syekh Arsyad melalui kitab-kitab fiqhnya tak banyak berlanjut di alam modern. Padahal, sisi ini penting untuk diangkat untuk menyambung kembali rantai intelektualitas umat Islam di Indonesia agar bisa berkontribusi untuk dunia. Arsyad Al-Banjari adalah ulama paling terkemuka di Tanah Banjar, mufti besar Kesultanan Banjar pada era Sultan Tahmidullah II.
Beliau dididik di tanah Banjar dan, atas beasiswa Kesultanan pada masa itu, disekolahkan ke Mekkah. Era itu, menurut kajian Azyumardi Azra, memang merupakan masa kejayaan intelektual muslim nusantara karena adanya jaringan ulama Jawi di tanah suci. Syekh Arsyad kemudian menjadi bagian penting dari tradisi intelektual tersebut. Setelah 30 tahun menuntut ilmu di tanah suci, ia kembali ke tanah Banjar.
Sekembalinya ke nusantara, Syekh Arsyad diberi sebidang tanah oleh Sultan untuk membangun tempat pengajaran –yang kita kenal sekarang sebagai “pesantren”. Bertempat di desa Dalam Pagar, Martapura, beliau mendirikan fondasi pemikiran mazhab Syafi’i yang khas Banjar, dengan basis pesantren yang ia dirikan serta produktivitas penulisan kitab-kitab fiqh. Dalam Pagar segera menjadi arena produksi pengetahuan pada masanya.
Sejauh ini, Syekh Arsyad mewariskan beberapa kitab penting antara lain Tuhfaturraghibien yang menjadi rujukan dalam masalah aqidah, Faraidl yang membahas soal hukum waris, Parukunan yang banyak mengupas soal ibadah. Tentu tak ketinggalan masterpiece: kitab Sabilal Muhtadin yang membahas secara komprehensif persoalan fiqh dan hal-hal kemasyarakatan lain. Sabilal Muhtadin (judul lengkapnya: Sabilal Muhtadin lit-Tafaqquh fi Amriddin) menjadi sebuah penanda bahwa Islam Nusantara pernah menjadi “pusat” dari pengkajian Islam di dunia. Ditulis pada 1779 M dalam bahasa Jawi, kitab ini tersebar luas ke jaringan pesantren di seluruh nusantara, Malaysia, hingga Thailand Selatan. Kitab ini menjadi semacam textbook untuk memahami fiqh dalam mazhab Syafii yang dipelajari oleh santri di pondok-pondok pesantren, bahkan hingga saat ini.
Hal ini membuktikan, dalam bidang ilmu-ilmu agama, Banjar pernah menjadi salah satu lokus keilmuan yang dipertimbangkan di Asia Tenggara dalam mazhab syafi’i (ditambah dengan Syekh Nafis Al-Banjari di bidang tasawuf). Islam Nusantara sudah mengglobal bahkan sebelum ASEAN dicanangkan. Pada titik inilah pembicaraan mengenai “Islam Nusantara” menjadi relevan di alam modernitas yang kian kompleks. Ada beberapa peneliti yang menulis tentang Syekh Arsyad. Sebut saja, misalnya, Darliansyah Hasdi yang meneliti metode istinbath hukmi (epistemologi hukum Islam) yang digunakan oleh Syekh Arsyad. Upaya Darliansyah Hasdi sangat patut diapresiasi karena memudahkan kita untuk melihat rantai intelektualitas yang sudah coba disambungkan oleh Syekh Arsyad.
Dalam catatan Darliansyah Hasdi, walaupun Syekh Arsyad adalah seorang penganut Mazhab Syafi’i, caranya menetapkan hukum ternyata tidak 100 persen menggunakan ka’idah syafi’iyah, melainkan juga menggunakan kaidah lain yang dikombinasikan secara kreatif sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya, dalam hal memakamkan mayat dengan menggunakan tabela (peti mati), ia menyatakan “boleh” jika tanah tempat makam tersebut rupuy atau berair (fenomena sering terjadi di Banjarmasin yang tanahnya tidak cukup liat).
Menurut Darliansyah, metode pengambilan hukum tersebut dilakukan secara induktif atau kontekstual, tidak melulu terpaku pada teks. Fatwa Syekh Arsyad memakamkan mayat dengan tabela tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan jenazah tanpa harus khawatir jika terjadi hujan. Artinya, beragama dimaknai sebagai sesuatu yang fleksibel namun tetap bersandar pada metode pengambilan hukum yang sah sesuai dengan kaidah fiqh. Apa yang bisa kita tangkap dari fakta tersebut?
Membaca Syekh Arsyad Al-Banjari bukan sekadar membaca “produk hukum” dari fatwafatwanya lantas mengamalkannya secara fanatik –apalagi kemudian menyalahkan orang yang “berbeda”. Syekh Arsyad memberi fondasi untuk beragama sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan kata lain, menjadikan agama sebagai sesuatu yang mudah untuk diamalkan oleh masyarakat dan tidak serta-merta ‘fanatik’ terhadap teks dan memaksakannya.
*Peneliti di ASEAN Studies Center UGM, dan penulis buku “Puasa dan Transformasi Sosial” (2015)